BAB
I
PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
Abad ini telah menjadi saksi adanya
dorongan yang besar bagi perkembangan hukum internasional di banding dengan
yang terjadi pada tahap sebelumnya dari sejarah hukum internasional ini.hal
tersebut merupakan akibat wajar dari berkembanya interdependensi negara-negara
dan peningkatan pesat hubungan-hubungan antar negara negara karena berbagai
macam penemuan yang di tunjukan guna menagulangi kesulitan-kesulitan menyangkut
waktu,ruang dan komunikasi.[1]
Sistem hukum internasional modern
merupakan suatu produk,kasarnya dari empat ratus tahun terakhir ini yang
berkembang dari adat istiadat dan praktek-praktek negara-negara eropa modern
dalam hubungan-hubungan dan komunikasi-komunikasi mereka.[2]
Hukum internasional sendiri berkembang
sangat pesat setelah berakhirnya perang dunia ke II dengan tujuan utama untuk
mengadili para penjahat perang nazi seperti Herman Goring, Heinric himler dan
beberapa penjahat nazi lainya lewat Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg
yang di bentuk oleh sekutu sebagai pemenang perang antara lain Amerika
Serikat,Uni Soviet, Inggris dan Perancis selain itu sekutu juga mendirikan
Mahkamah Internasional Timur Jauh, atau dikenal dengan Mahkamah Tokyo, juga
merupakan mahkamah yang didirikan untuk mengadili penjahat perang
Pengadilan ini sendiri memiliki tujuan
untuk menyelidiki pelanggaran HAM yang di lakukan oleh para pejabat serta
jendral perang nazi dan jepang yang terjadi di negara-negara yang di duduki
oleh nazi dan jepang lewat kejadian yang kita kenal sebagai holocaust yaitu suatu pemusnahan
besar-besaran kaum yahudi oleh nazi dan perbudakan oleh pihak jepang.
Konsepsi negara-negara Barat dari semula
telah medominasi pemikiran negara-negara yang tergabung dalam PBB waktu
mereka,seusai perang dunia ke II (1942-1945) yang amat dahsyat itu,ingin
merumuskan suatu dokumen hak asasi manusia yang dapat di terima secara
universal.[3]
Hampir setengah abad
setelah Perang Dunia berakhir, masyarakat internasional kembali dikejutkan
dengan praktek pembersihan etnis yang lagi-lagi terjadi di Eropa yakni di
Negara bekas Yugoslavia. Konflik di Bosnia-Herzegovina, sejak April 1992 dan
berakhir bulan November 1995, merupakan praktek pembersihan etnis yang
kekejamannya sudah mencapai tingkat yang tidak pernah dialami Eropa sejak
Perang Dunia II. Kamp-kamp konsentrasi, perkosaan yang sistematis, pembunuhan
besar-besaran, penyiksaan, dan pemindahan penduduk sipil secara massal adalah
bukti-bukti yang tidak dapat diingkari yang akhirnya mendorong Dewan Keamanan
PBB untuk mendirikan International Criminal Tribunal for The Former
Yugoslavia (ICTY) dengan pertimbangan bahwa sudah meluasnya tindakan
pelanggaran terhadap hukum humaniter termasuk praktek pembersihan etnis
sehingga sangat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.[4]
Berbagai kritikan
kembali muncul seiring terbentuknya ICTY ini, banyak kalangan yang menganggap
bahwa mahkamah ini hanyalah kebetulan belaka dan hanya menjadi alat bagi
negara-negara adikuasa seperti halnya Amerika Serikat untuk memuluskan langkah politiknya
dalam politik negara lain di sisi lain pembentukan ICTY jauh dari objektifitas
hukum karena yang mengadili adalah negara-negara yang memiliki kepentingan di
negara tersebut sebagai akibat belum adanya hukum internasional atau peraturan
mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Indonesia sendiri telah mengalami
berbagai macam pelanggaran HAM seperti peristiwa 1965,
Semanggi I, Semanggi II, Tragedi Trisakti, Peristiwa Talangsari, Peristiwa
Tanjung Priok, Penembak Misterius, Penculikan Aktivis 1998, Kasus-Kasus di
Papua dan Aceh, Timor Leste yang membuat kejadian-kejadian tersebut merubah
perspektif dan paradigma masyarakat tentang perlindungan dan pertanggungjawaban
penyelesain peristiwa pelanggaran HAM akan tetapi dengan banyaknya korban jiwa
tidak membuat banyak pelaku pelanggar HAM dapat di seret di pengadilan sebagai
akibat masih kuatnya praktek impunitas di Indonesia.
Kasus
Semanggi merupakan salah satu kasus dimana terjadi suatu pelanggaran HAM berat
yang dilakukan oleh kalangan militer yang melakukan penyerangan terhadap
mahasiswa dengan peluru tajam dalam hal ini milter telah melakukan Kejahatan
Terhadap Kemanusia dan dapat diadili dengan Asas Pertanggungjawaban Komando.
Peristiwa Semanggi I. Mahasiswa berdemonstrasi untuk menolak
sidang istimewa yang dinilai inkonstitusional serta meminta presiden untuk
mengatasi krisis ekonomi. Delapan belas orang meninggal karena ditembak aparat,
lima orang diantaranya adalah mahasiswa, yaitu Teddy Mardani, Sigit Prasetya,
Engkus Kusnadi, Heru Sudibyo dan BR Norma Irmawan. Korban yang luka-luka
sebanyak 109 orang, baik masyarakat maupun pelajar. [5]
Peristiwa Semanggi II. Mahasiswa berdemonstrasi merespon
rencana pemberlakuan UU Penanggulangan Keadaan Bahaya, karena dianggap bersifat
otoriter tak jauh dari UU Subversif. Aparat keamanan kembali melakukan
penembakan kepada mahasiswa, relawan kemanusiaan, tim medis dan masyarakan yang
menimbulkan 11 orang meninggal di seluruh Jakarta, salah satunya adalah Yap Yun
Hap di bilangan Semanggi Jakarta. Korban luka-luka mencapai 217 orang.
Represifitas aparat juga diberlakukan kepada mahasiswa-mahasiswa seluruh
Indonesia, tiga orang mahasiswa diantaranya, yaitu Yusuf Rizal (mahasiswa
Bandar Lampung) dan Saidatul Fitira (mahasiswadi Lampung) serta Meyer Ardiansah
(mahasiswa IBA Palembang).[6]
Harapan kasus Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II untuk menggelar pengadilan HAM ad hoc bagi para oknum tragedi berdarah itu dipastikan gagal
tercapai. Badan Musyawarah
(Bamus) DPR pada 6 Maret 2007
kembali memveto rekomendasi tersebut. Putusan tersebut membuat usul pengadilan
HAM kandas, karena tak akan pernah disahkan di rapat paripurna.
Putusan penolakan dari Bamus itu merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya Bamus
telah menolak, namun di tingkat rapim DPR diputuskan untuk dikembalikan lagi ke
Bamus.[7]
Pemerintah dalam hal ini DPR tidak mempunyai tujuan baik dalam
penyelesain kasus semanggi dimana DPR sebagai wakil rakyat tidak memberikan
suatu keadilan bagi penyelesain kasus semanggi yang membuat impunitas yang ada
di Indonesia semakin menggurita dan pelaku pelanggaran HAM berat tetap bebas
dan tidak di adili di depan Pengadilan karena Indonesia harus lebih proaktif
dalam penegakan hukum dengan salah satunya dapat mengadopsi atau meratifikasi
instrumen hukum tentang penegakan HAM di Indonesia salah satunya ialah Statuta
Roma tahun 1998.
Masih kuatnya praktek impunitas di
Indonesia sebagai akibat belum terlaksananya secara maksimal Asas
Pertanggungjawaban Komando biasanya dalam penaganan kasus pelanggaran HAM serta
penyelesainya hanya fokus kepada pelaku yang melakukan pelanggaran secara
langsung atau fisik akan tetapi para pejabat terkait dan atasan mereka tidak di
bebankan pelanggaran HAM walaupun mereka tidak melakukan secara fisik tetapi
mereka mengetahui dan ikut memerintahkan karena hal tidak mungkin seorang
prajurit melakukan suatu operasi tanpa sepengatahuan atau perintah dari atasan.
Dalam perkembanganya sebagai akibat
belum adanya suatu peraturan Mengenai Hak Asasi Manusia secara universal
akhirnya PBB berinisiatif untuk membentuk suatu peraturan dan pembentukan
lembaga permanen yang mengadili tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
bertujuan untuk supermasi hukum dan keadilan dalam penaganan Kasus pelanggaran
HAM.
Pada 17
Juli 1998, 120 negara yang berpartisipasi dalam “United Nations Diplomatic
Conference on Plenipotentiaries on the Establishment of an International
Criminal Court menyetujui dibentuknya International Criminal
Court (ICC) yang diadopsi dari Statuta Roma tersebut.Pengadilan Pidana Internasional (ICC = The International Criminal Court) merupakan sebuah
lembaga yudisial independen yang permanen, yang diciptakan oleh komunitas
negara-negara internasional, untuk mengusut kejahatan yang mungkin dianggap
sebagai yang terbesar menurut hukum internasional seperti: genosida, kejahatan
lain terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.[8]
Statuta
Roma menjadi tonggak sejarah dalam penegakan pelanggaran HAM di berbagai negara
akan tetapi Indonesia sebagai negara yang telah berkomitmen dalam penegakan
pelanggaran HAM belum melakukan Ratifikasi Statuta Roma padahal hal ini telah
tercantum dalam Rencana
Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranhamnas) 2004 – 2009[9]
dan remhamnas 2009-2014[10],
akan tetapi Ratifikasi masih belum di lakukan padahal Ratifikasi Statuta Roma
menjadi hal sangat Urgen dalam penegakan HAM di Indonesia dalam menghapusankan
berbagai praktek impunitas yang terjadi di Indonesia sebagai legitimasi rakyat
untuk mecapai suatu keadilan padahal UUD 1945 telah jelas
mengatur dan melindungi HAM rakyat Indonesia, dan dalam pasal 28 I ayat 4
dinyatakan:[11]
“Perlindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab
negara, terutama pemerintah.”
Dalam hal ini sudah
sangat jelas negara harus berperan aktif dalam melindungi warga Negara dari
pelanggaran HAM memang Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 26 tahun 2000
tentang Pengadilan HAM yang adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak
asasi manusia yang berat.[12]
Pengadilan ini bersifat ad hoc (sementara) dan mampu mengadili
kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau. Namun jika di lihat dari
fakta di lapangan banyak pelaku pelanggaran HAM berat tidak pernah di periksa
akibatnya timbulnya Impunitas terhadap pelaku Pelanggaran HAM padahal
pelanggaran HAM Bukan hanya mengenai kontak fisik tetapi ada pula asas
Pertanggujawan Komando yang sangat efektif dalam menjerat para pelaku kejahatan
Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan latar
belakang tersebut penulis berkeinginan meneliti dan memberikan sebuah gagasan
dengan judul ”KAJIAN YURIDIS TERHADAP
ASAS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO (SUATU TINJAUN KRITIS TERHADAP KASUS SEMANGGI)”
1.2.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka
yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana
Kajian Yuridis terhadap Asas Pertanggungjawaban Komando?
2. Bagaimana
mengkonstruksi Statuta Roma dalam hal penerapan asas Pertanggungjawaban Komando
di Indonesia?
1.3. Tujuan Penelitian
Adapun
tujuan penelitian berdasarkan
permasalahan diatas antara
lain sebagai berikut:
1. Untuk
dapat mengentahui dan menganilisis Asas Pertanggungjawaban Komando
2. Untuk
dapat mengetahui dan menganalisis penerapan asas Pertanggungjawaban Komando di
Indonesia menurut Statuta Roma
1.4.
Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian hukum
berdasarkan tujuan penelitian diatas anatara lain sebagai berikut.
1.4.1.
Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat
mengembangkan konsep tentang HAM dan Ratifikasi Statuta Roma di tinjau dari
Praktek Impunitas dan Pertanggungjawaban Komando.
1.4.2.
Manfaat Praktis
Adapun
manfaat praktis dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1.4.2.1.
Bagi Peneliti
Agar dapat mengetahui,
mengerti dan memahami bagaimana Proses penegakan HAM di Indonesia, Manfaat
Ratifikasi Statuta Roma oleh indonesia,dan praktek impunitas serta
Pertanggungjawaban Komando di Indonesia
1.4.2.2.
Bagi Masyarakat
Memberikan pemahaman
serta pengetahuan yang objektif tentang Ratifikasi Statuta Roma oleh Indonesia
dalam menghapus praktek Impunitas dan penegakan Pertanggungjawaban Komando.
1.4.2.3.
Bagi Pemerintah
Memberikan dorongan
moral agar dapat Meratifikasi Statuta Roma sebagai landasan untuk penyelesain
kasus pelanggaran HAM.
1.4.2.4.
Bagi Akademisi
Dapat dijadikan sebagai
bahan rujukan dan kajian ilmiah tentang penggunaan Ratifikasi Statuta Roma
dalam penghapusan Praktek Impunitas dan Penegakan Asas Pertanggungjawaban
Komando.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Tinjauan Filosofis
2.1.1.
Pengertian Kajian Yuridis
Kajian berasal dari kata mengkaji menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belajar, mempelajari,
memeriksa, menyelidiki, memikirkan mempertimbangkan dan sebagainya, menguji
menelaah baik buruk suatu perkara.[13] Selanjutnya menurut Kamus Hukum kata
Yuridis berasal dari kata Yuridisch
yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.[14] Dapat disimpulkan Kajian yuridis berarti mempelajari
dengan cermat, memeriksa untuk memahami suatu pandangan atau pendapat dari segi
hukum.
2.1.2.
Pengertian Pertanggungjawaban
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab yaitu keadaan wajib
menanggung segala sesuatunya kalau terjadi apa-apa boleh dituntut,
dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya.[15]
Roeslan
Saleh berpendapat bahwa:[16]
Pertanggungan jawab itu dinyatakan dengan
adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan
akibat-akibat hukum yang disyaratkan. Hubungan antara keduanya ini tidak
bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan oleh aturan
hukum. Jadi pertanggungan jawab itu adalah pernyataan dari suatu keputusan
hukum.
Uraian konsep ”pertanggungjawaban” (liability), dilihat
dari segi falsafah hukum selanjutnya lebih dipertegas oleh seorang filosof
besar dalam bidang hukum pada abad ke 20, yaitu Rouscou Pound, dalam ”AnIntroduction
to the Philosophy of Law”, yang mengemukakan pendapat bahwa :[17]
”I ... use the simple word
”liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally
subjected to the exaction”
Teori pertama, menurut Pound bahwa liability diartikan
sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku
dari seseorang yang telah dirugikan.
Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap
kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya
keyakinan bahwa pembalasan sebagai
suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti
rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban. Berdasarkan hal tersebut maka, konsepsi liability diartikan
sebagai ”reparation”, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi ”liability”
dari ”composition for vengeance” menjadi ”reparation for injury”.
Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan
penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari ”liability” atau
”pertanggungjawaban”.[18]
Perkembangan konsep Pertanggungjawaban dalam dunia hukum
kontemporer menjadi suatu hal yang sangat urgen pertanggunjawaban bukan saja
dapat di artikan sebagai bagian menganti suatu materi atas kerugian yang
dialami tapi lebih mengarah kepada tindakan apa yang telah dilakukan seseorang
sehinga dapat di jatuhi hukuman.
Selanjutnya Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk dikatakan bahwa
seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban
seperti berikut:[19]
a.
Melakukan
perbuatan pidana (sifat melawan hukum)
b.
Di atas
umur tertentu mampu bertanggungjawab
c.
Mempunyai
suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
d.
Tidak
adanya alasan pemaaf.
Dari berbagai Pengertian di atas dapat
di simpulkan bahwa Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan
atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat
sikapnya oleh pihak lain.
2.2.
Pengertian
Dan perkembangan Tanggung jawab Komando Terhadap Pelanggaran HAM yang Berat Dan
Kejahatan Perang Dalam Hukum Internasional
2.1.1. Pengertian Tanggung jawab Komando Menurut Hukum Internasional
Berbicara tentang konsep pertanggungjawaban komando berlaku bagi
seorang atasan dalam pengertian yang luas, termasuk kepala negara, kepala
pemerintahan, menteri dan pimpinan perusahaan. Dalam doktrin hukum
Internasional mengenai pertanggungjawaban komando adalah doktrin yang
berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang
dikembangkan melalui kebiasaan dan praktek-praktek pengadilan kejahatan perang,
terutama seusai perang dunia ke-II.
Hugo Grotius menggunakan analogi ”tanggung jawab orang tua” (parental
responsibility) untuk menggambarkan pertanggungjawaban komando:[20]
“Orang tua bertanggung jawab terhadap
kesalahan anaknya sepanjang anaknya masih ada dalam kekuasaan mereka. Di
sisi lain, walaupun orang tua memiliki anak yang berada di bawah
kekuasaannya namun orang tua tersebut tidak mampu lagi untuk
mengendalikan mereka, maka orang tua tersebut tidak lagi harus
bertanggung jawab kecuali jika ia memiliki pengetahuan. Jadi dalam hal
ini seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban atas tindakan yang
dilakukan oleh orang lain apabila memenuhi dua elemen, yaitu (1)
pengetahuan (2) gagal untuk mencegah.”
Dalam Protokol
Tambahan I Konvensi Jenewa 1977 asas Pertanggungjawaban Komando di atur dengan
jelas pada Pasal 86 ayat (2) AP I berbunyi :[21]
“The
fact a breach of the conventions or of this Protokol was committed by a
subordinate does not absolve his duperiors from penal or disciplinary, as the
case may be, if they knew, or had information which should have enabled them to
conclude in the circumstances at the time, that he was committing or was going
to commit such a breach and if they did not all feasible measures within their
power to prevent or repress the breach”.
Pasal
ini tidak menciptakan suatu aturan hukum baru, tetapi menjelaskan tentang
aturan hukum kebiasaan bahwa pelanggaran dapat timbul sebagai akibat dari tidak
dilakukannya suatu kewajiban. Pasal 86
ayat (2) menetapkan tanggung jawab seorang atasan dalam kaitannya dengan
tindakan yang dilakukan oleh bawahannya.
Dalam hal ini atasan wajib melakukan intervensi dengan cara mengambil
semua lengkah yang memungkinkan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk mencegah,
atau menindak pelanggaran tersebut.
Selanjutnya dalam
Statuta International Criminal Court (ICC) Pasal 28 huruf (a) Statuta ICC menyatakan:[22]
Seorang komandan militer atau orang yang secara efektif
bertindak sebagai komandan militer bertanggung jawab secara kriminal atas
kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan yang dilakukan oleh pasukan
yang berada di bawah komando dan kendalinya secara efektif, sebagai akibat
kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang semestinya terhadap pasukan
tersebut, dalam hal :
a.
Bahwa komandan militer mengetahui
atau berdasarkan keadaan yang berlangsung saat itu, mesti telah mengetahui
bahwa pasukannya sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan.
b.
Bahwa komandan militer tidak
berhasil mengambil semua tindakan yang semestinya dan diperlukan sesuai
kewenangannya untuk mencegah atau menindak terjadinya kejahatan atau mengajukan
pelanggaran tersebut kepada lembaga yang berwenang dibidang penyelidikan dan
penuntutan.
Berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan yang tidak
tercakup dalam pasal di atas, pasal 28 huruf (b) menyatakan seorang atasan
bertanggung jawab secara kriminal atas kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan
yang dilakukan oleh bawahan yang berada di bawah kekuasaan dan kendali
efektifnya, sebagai akibat kegagalannya dalam menjalankan pengendalian yang
semestinya terhadap bawahan tersebut, dalam hal :[23]
a.
Atasan mengetahui, atau secara sadar
mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bawahannya sedang
melakukan atau akan melakukan kejahatan.
b.
Kejahatan tersebut berkaitan dengan
kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggung jawab dan pengendalian atasan
secara efektif.
c.
Atasaan gagal mengambil semua upaya
yang semestinya dan diperlukan sesuai kewenangannya untuk mencegah dan menindak
terjadinya kejahatan atau mengajukan pelanggaran tersebut kepada lembaga yang
berwenang di bidang penyelidikan dan penuntutan.
Perintah
seorang Komandan yang di maksudkan adalah perintah yang tidak bertentangan
dengan hukum, apabila perintah tersebut (eksplisit maupun implisit) bertentangan
dengan hukum maka komandan (atasan) dan bawahan harus bertanggungjawab secara
hukum. Hal lain dapat terjadi perintah seorang komandan, atasan atau pejabat
berwenang subtansinya di luar kewenanganya, sehingga di katakan sebagai
penyimpangan kekuasaan (abuse of power)
sebagai salah satu sumber pelanggaran hukum bawahan.[24]
Secara
prinsip komandan atau atasan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dalam
dua kategori. Pertama, tanggung jawab muncul karena adanya tindakan pelanggaran
hukum yang dilakukan komandan dalam merespon situasi dalam hal ini berupa
keterlibatan komandan atas perintah dan perencanaanyang mengakibatkan bawahan
melakukan pelanggaran hukum. Kategori pertama yang dikenal dengan tanggungjawab
komando secara langsung (vicariuos
atau direct command liability).[25]
Kedua
seorang komandan atau atasan bertanggung jawab secara pidana karena tidak
melakukan tindakan apapun sesuai dengan kewenangan dan kekuasaan yang
dimilikanya. Komandanmembiarkan terjadi pelanggaran hukum (omission) bawahanya atau tidak mengambil upaya yang tepat untuk
menghentikan dan menindak bawahanya sebagai pelaku kejahatan. Tanggung jawab
komandan dalam hal ini adalah tanggung jawab komando yang bersifat tidak
langsung (indirect command responsibility
atau imputed liability).[26]
Dari
berbagai urain di atas dapat di simpulkan bahwa Pertanggungjawaban komando
adalah suatu mekanisme untuk menghukum para atasan sebagai akibat pembiaran
yang dilakukan atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya, dimana
atasan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui kejahatan yang dilakukan
oleh bawahannya khususnya dalam pelanggaran HAM berat dimana atasan mempunyai
kendali efektif (kesalahan dari atasan ataupun komandan tersebut). Bentuk
kesalahannya adalah mengetahui atau sepatutnya mengetahui tetapi tidak
mengambil tindakan-tindakan hukum berupa pencegahan, penanganan dan tidak
melaporkannya. Komandan atau atasan tersebut yang harus melapor adalah bentuk
kewajibannya.
2.1.2.Perkembangan
Tanggung Jawab Komando Terhadap pelanggaran HAM yang berat Dan Kejahatan Perang
Dalam Hukum Internasional.
Perkembangan Tanggung Jawab Komando
mencapai puncaknya saat pecah perang dunia ke II sebagai akibat timbulnya suatu
tindakan yang luar biasa kejam terhadap manusia yang membuat para pemimpin
dunia memandang perlu adanya pengaturan lebih lanjut atas kejahatan ini akan
tetapi perkembangan tanggung jawab komando telah berkembang beberapa abad
sebelumnya di eropa. Dari ketentuan-ketentuan yang mengatur
mengenai tanggung jawab komando serta proses hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus
tersebut, akan dikemukakan elemen-elemen pokok yang menjadi dasar penentuan
kesalahan seorang komandan atau atasan atas dasar doktrin tanggung jawab
komando atau tanggung jawab atasan.
Mulanya, Raja Charles Vll dari Perancis di Orleans pada tahun 1493
mengeluarkan perintah yang tegas berkaitan dengan doktrin tanggung jawab
komando. Perintah tersebut menyatakan:[27]
”Raja memerintahkan bahwa setiap kapten
atau letnan bertanggung jawab atas penyimpangan, tindakan buruk dan pelanggaran
yang dilakukan oleh anggota kompinya, dan setelah ia menerima suatu pengaduan
mengenai adanya kesalahan atau penyimpangan tersebut, ia membawa pelakunya ke
pengadilan sehingga pelakunya dihukum sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya.
Jika ia tidak melakukan hal itu atau menutupi kesalahan atau tidak mengambil
tindakan, atau jika, karena kelalainnya atau kesengajaannya pelaku kejahatan
melarikan diri sehingga terhindar dari hukuman, kapten tersebut harus dianggap
bertanggung jawab atas kejahatan tersebut seolah-olah ia telah melakukan
sendiri kejahatan itu dan harus dihukum sama seperti yang akan dijatuhkan
kepada pelaku kejahatan”.
Beberapa aspek penting mengenai doktrin tanggung jawab komando
yang terdapat dalam perintah raja Charles tersebut adalah: pertama, komandan
bertanggung jawab untuk mengendalikan perilaku termasuk cara bertindak yang
dilaksanakan oleh bawahannya agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang
berlaku; kedua, komandan berkewajiban untuk memproses setiap bawahannya
yang terlibat sebagai pelaku kejahatan secara hukum; ketiga, jika
komandan karena kelalaian atau kesengajaan membiarkan kejahatan terjadi dan
tidak melakukan kedua hal tersebut di atas, maka ia bertanggung jawab secara
pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh prajurit bawahannya.[28]
Lebih jelas lagi perkembangan doktrin tanggung jawab komando ini,
diberlakukan oleh Adolphus Gustavus ketika pada abad VII tahun 1621 ia
mengeluarkan suatu ketentuan yang dikenal sebagai pasal-pasal menegenai perang
(the articles of war). Diantaranya Pasal 46 yang menegaskan bahwa:[29]
”seorang kolonel atau kapten tidak boleh memberikan
komando kepada prajuritnya untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan
dengan hukum; siapa yang melakukan yang demikian itu harus dihukum berdasarkan
keputusan hakim”.
Setelah itu doktrin pertanggungjawaban komando diatur dalam instrumen
hukum Humaniter Internasional. Yang pertama yaitu dalam The Regulation
Annexed to 1907 Haque Convention IV mengenai penghormatan terhadap hukum
dan kebiasaan dalam perang di darat. Di dalam Regulation ini dikatakan bahwa
sebagian dari hukum, hak-hak dan kewajiban dalam perang yang berlaku bagi
angkatan bersenjata, juga berlaku bagi para milisi dan korps sukarelawan.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh milisi dan korps sukarelawan,
agar dapat dikategorikan sebagai kombatan yang sah, antara lain yakni harus dipimpin
oleh orang yang bertanggungjawab terhadap anak buahnya dan melaksanakan operasi
militer berdasarkan hukum dan kebiasaan dalam hukum perang. Dari ketentuan Regulation
ini dapat dilihat adanya aspek tanggung jawab sebagai salah satu syarat
seseorang atau sekelompok orang untuk dapat dikatakan sebagai kombatan.[30]
Pengaturan tanggung jawab komando terdapat dalam Pasal 3 Konvensi
Den Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat. Ayat (1) dari
Pasal 3 Konvensi Den Haag IV 1907 ini mengatakan bahwa setiap pihak yang
bersengketa yang melanggar ketentuan hukum perang bertanggung jawab untuk membayar
kompensasi jika kasusnya menghendaki demikian. Kemudian ayat (2) dari pasal
yang sama mengatur bahwa pihak yang bersengketa bertanggung jawab terhadap
setiap tindakan yang dilakukan oleh anggota angkatan bersenjatanya.[31]
Melihat ketiga Konvensi tersebut terdapat pengaturan tentang tanggung
jawab negara dan khususnya para Komandan berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi
Jenewa 1949. Hal yang sama juga terdapat dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Konvensi
jenewa I Tahun 1949 yang mengatur tentang tanggung jawab negara untuk
menjatuhkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran berat hukum humaniter.[32]
Dalam sejarah peradilan internasional, masalah tentang tanggung jawab
komando ini juga diterapkan dalam Pengadilan Nuremberg dan Pengadilan Tokyo
terhadap pelaku kejahatan perang dari Nazi Jerman seperti telah di jelaskan di
atas bahwa asas pertanggungjawaban komando mencapai pucaknya pada saat perang
dunia ke II saat itu sekutu mengadili penjahat perang nazi dan jepang dalam
suatu pengadilan yang bersifat ad hoc untuk
mempertanggungjawabkan perbuatan saat perang.
Adapun pengadilan Nurenberg dibentuk berdasarkan piagam Nurenberg
atau piagam London. Didalam Piagam London ini ditetapkan tiga kategori
pelanggaran atau kejahatan yang menjadi yuridiksi dari mahkamah Nurenberg
yaitu; kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang),dan kejahatan terhadap
kemanusiaan. Yuridiksi Mahkamah tersebut diatur dalam Pasal 6 piagam
Nurenberg.[33]
Dengan melihat kedua mahkamah tersebut (Nurenberg serta Tokyo)
dapat dijelaskan bahwa apabila terjadi suatu kejahatan maka tanggung jawab
berlaku bagi para pemimpin, organisator, pemicu dan penyerta yang ikut serta
dalam merumuskan, atau melaksanakan rencana umum atau konspirasi untuk
melakukan setiap kejahatan. Baik pihak yang memberi perintah dan yang
malaksanakan perintah sama-sama bersalah melaksanakan kejahatan. Apabila
Komandan yang bersangkutan tidak memerintahkan (memberi perintah secara
langsung) kejahatan tersebut tetapi ia mengetahui atau semestinya mengetahui
tindakan yang melanggar hukum dan tidak mengambil tindakan yang semestinya maka
komandan tersebut dapat dihukum.
Kemudian konsep tanggung jawab komando ini diatur dalam ICTY (International
Criminal tribunal for the former Yugoslavia) dan ICTR (Rwanda) serta ICC.
Dalam ICTY tanggungjawab komando diatur dalam Pasal 7 ayat (3) yang menegaskan
bahwa seorang komandan dapat dikenakan tanggung jawab mengenai kejahatan yang
dilakukan oleh prajuritnya yang berada dibawah komandonya jika ia
memerintahkan, atau menyadari atau memiliki alasan untuk mengetahui bahwa
bawahannya akan melakukan kejahatan serta ia gagal untuk mengambil langkah yang
diperlukan dan pantas guna mencegahnya. Hal yang sama juga dipertegas dalam
Pasal 6 ayat (3) ICTR.[34]
Pada saat itu slobodan milosevic Selama Perang Kosovo Milošević dikenai tuduhan pada 27 Mei 1999, atas kejahatan
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di Kosovo. Ia diadili hingga kematiannya di International Criminal Tribunal for the
Former Yugoslavia, yang
dinyatakannya tidak legal, karena dibentuk berlawanan dengan anggaran dasar
PBB.[35]
Istilah ”kejahatan terhadap kemanusiaan” (Crime Against
humanity) bermula sejak dikembangkan Petersburg Declaration tahun
1868. Namun perumusan kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri belum
dirumuskan dalam declaration tersebut, melainkan perumusan tersebut terdapat
dalam konvensi Den Haag 1907 (Haque Convention), yang merupakan
kodifikasi dari hukum kebiasaan mengenai konflik bersenjata. Dalam
konvensi tersebut istilah kejahatan terhadap kemanusiaan memakai istilah
”hukum kemanusiaan”(laws of humanity). Konvensi ini menyatakan
bahwa hukum kemanusiaan (laws of humanity) merupakan dasar
perlindungan bagi pihak kombantan maupun penduduk sipil dalam suatu konflik
bersenjata. Adapun kodifikasi ini didasarkan kepada praktek negara yang
diturunkan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dianggap sebagai hukum
kemanusiaan berdasarkan sejarah dari berbagai kebudayaan.[36]
Seusai Perang Dunia ke-II, pengadilan militer Internasional
(International Military Tribunal/IMT) di Nurenberg memisahkan antara kejahatan
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 6 Piagam London (London
charter) merumuskan kejahatan perang (war crimes) sebagai
pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang meliputi antara lain
pembunuhan, perlakuan kejam, atau deportasi secara paksa untuk dijadikan budak,
yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Sedangkan yang termasuk kejahatan
terhadap kemanusiaan termasuk didalamnya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan,
deportasi dan perbuatan yang tidak menusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk
sipil, baik yang dilakukan sebelum atau ketika perang berlangsung. Kejahatan
terhadap kemunusiaan ini juga meliputi penyiksaan terhadap penduduk sipil yang
didasarkan pada alasan-alasan politik, rasial dan agama.[37]
Perkembangan hukum Internasional untuk memerangi kejahatan terhadap
kemanusiaan mencapai puncaknya ketika pada tanggal 17 Juli 1998, yakni pada
waktu konferensi diplomatik PBB mengesahkan Statuta Roma tentang pendirian
mahkamah pidana Internasioanal (Rome Statute on the establishments of
the International Criminal Court/ICC), yang akan mengadili pelaku kejahatan
yang amat serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional, yaitu
kejahatan terhadap kemanusiaan, genoside dan kejahatan perang.[38]
2.3.
Pembaharuan Sistem Hukum Indonesia Untuk Penegakan Asas Pertanggungjawaban
Komando.
2.1.1.Pembentukan
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Istilah Pengadilan HAM untuk pertama kalinya
disebutkan secara formil dalam Bab IX tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
Pasal 104 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang
HAM. UU ini menyatakan bahwa pengadilan HAM dibentuk untuk mengadili
pelanggaran HAM yang berat, seperti pembunuhan masal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan
pengadilan (arbitary/extra judicialkilling), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa,
perbudakan atau diskriminasi yang
dilakukan secara sistematis (systematic
discrimination) yang sesuai dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 rome statute of the international criminal court.[39]
Peraturan Perundang-undangan ini menjadi
tonggak sejarah tersendiri bagi Indonesia yang baru menyelesaikan undang-undang
ini di tenha kekacaun politik yang melanda waktu itu. Undang-undang No 39 tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti menjadi nafas baru serta harapan baru
demi terwujudnya Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Perpu tersebut
sesungguhnya dipersiapkan pemerintah dalam keadaan tergesa-gesa, yaitu
sehubungan dengan terbentuknya opini umum, baik di dalam maupun luar negeri. Di
dalam dapat dilihat pada situasi politik waktu itu masyarakat mendesak dan
menghendaki pemerintah melalui pengadilan untuk segera mengadili pelaku-pelaku
pelanggaran HAM berat.
Di keluarkannya Perppu a quo kemudian dipandang sebagai solusi untuk memberikan kepastian
awal bagi masyarakat dan dunia internasional bahwa Indonesia memiliki kemauan
untuk memproses segala bentuk pelanggaran atau kejahatan HAM. Potret ini jika
dilihat dari aspek politik hukum, maka proses pembentukannya bertitik tolak
atas perkembangan hukum masyarakat dalam negeri dan dan masyarakat global,
dengan kata lain proses ini memiliki tendensi untuk kepentingan nasional agar
tetap eksis dalam percaturan dunia global. Apabila Indonesia tidak segera
merespon situasi politik pada saat itu, dapat dipastikan Indonesia yang telah
mentasbihkan diri bergabung dengan PBB akan dikucilkan dalam pergaulan dunia.
Hal ini mengingat PBB secara tegas menjunjung nilai universal HAM dan
berkomitmen menegakannya.
Mengingat masyarakat belum merasa puas jika
payung hukum pengadilan HAM hanya berdasarkan Perpu, maka masyarakatpun
mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Perpu a quo menjadi UU. Akhirnya pada tahun 2000 Perpu a quo disahkan menjadi Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Dengan demikian, pemberlakuan UU a quo merupakan bagian dari program
strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa Indonesia
dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM dengan sistem hukum nasional yang
berlaku dan proses pemgadilan dapat dilaksanakan oleh bangsa sendiri.[40]
Kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang
bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya
hukum tentang HAM itu dibuat untuk membangun masa depan yang lebih baik, yakni
kehidupan Negara yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran HAM terutama yang
dilakukan oleh penguasa.[41]
Pemerintah ketika hendak merumuskan atau
membuat aturan HAM harus memiliki pertimbangan matang dan koheren dengan
situasi politik yang ada. Maka dalam konteks UU tentang pengadilan HAM,
pertimbangan pemerintah dalam penyusunan UU pengadilan HAM (sebelumnya RUU)
adalah sebagai berikut:[42]
1. Merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa
Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan
demikian merupakan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan
melaksanakan Deklarasi Universal HAM yang ditetapkan oleh PBB, serta yang
terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur mengenai HAM yang
telah dan atau diterima oleh Negara Republik Indonesia;
2. Dalam rangka melaksanakan TAP MPR No.
XVII/MPR/1998 tentang HAM dan sebagai tindak lanjut dari UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM. Hal ini mengingat kebutuhan hukum yang sangat mendesak, baik
ditinjau dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan
internasional, maka segera dibentuk Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus
untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM yang berat.
3. Untuk mengatasi keadaan yang tidak menentu di
bidang keamanan dan ketertiban umum, termasuk perekonomian nasional. Keberadaan
Pengadilan HAM ini sekaligus diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan
masyarakat dan dunia internasional terhadap penegakan hukum dan jaminan
kepastian hukum mengenai penegakan HAM di Indonesia.
2.1.2.Kelemahan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Undang-undang tentang pengadilan HAM adalah
sebagai akibat tekanan internasional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM
pada tahun 1998 saat itu pemerintah membuat dengan terburu-buru dan kurang
memperhatikan subtansi dari Undang-undang yang di buat yang membuat banyak
produk undang-undang HAM menjadi Absurt
atau kabur mengakibatkan ketidakjelasan dalam menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia.
Pembentukan undang-undang a quo terjadi ketika terungkapnya fakta telah terjadi pelanggaran
HAM berat di Indoensia, sehingga muncul desakan dari PBB untuk segera diadili
pelaku-pelakunya. Mengingat waktu itu Indoensia belum mempunyai instrumen
hukumnya, maka muncul gagasan dari PBB agar pelakunya diadili melalui
pengadilan HAM internasional atau Mahakamah Internasional. Apabila hal itu
terjadi, maka yuridksi hukum nasional tidak ddigunakan dalam proses mengadili
pelaku-pelakunya. Sehingga sebagai langkah antisipasi, pemerintah membentuk Pepru
sebagai legitimasi pembentukan pengadilan HAM, kemudian disahkan menjadi UU No.
26 Tahun 2000. Proses tersebut jelas sangat mendadak dan terburu-buru karena
seolah-olah hanya dimaksudkan agar menghindarkan para pelaku pelanggaran HAM
berat dari jerat Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu juga diiringi motif
Indonesia untuk mengadili pelaku di Indonesia dengan hokum nasional yang ada.[43]
Adapun titik lemah dalam UU No 26 tahun 2000
tentang pengadilan Hak Asasi Manusia antara lain sebagai berikut, yaitu:
1.
Meluas
atau Serangan sistematis terhadap penduduk sipil ‟[44]
dalam Statuta Roma menjadi ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil[45],
padahal seharusnya berbunyi ditujukan
kepada populasi sipil. Kata “langsung” ini bisa berimplikasi pada seolah-olah hanya
pelaku di lapangan saja yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku
diatasnya yang membuat kebijakan tidak tercakup dalam pasal ini. istilah
“penduduk” untuk menerjemahkan kata “population” telah menyempitkan subyek
hukum dengan menggunakan batasan-batasan wilayah yang akan menyempitkan
target-target potensial korban kejahatan terhadap kemanusiaan hanya kepada
warga negara dimana kejahatan tersebut berlangsung.[46]
Hal diatas berkaitan erat dengan „delik tanggung-jawab komando‟ sebagaimana
yang diatur di dalam pasal 42 ayat 1 yang menyatakan :[47] “Komandan Militer atau seseorang yang secara
efektif bertindak sebagai komandan
militer dapat dipertanggungjawabkan
terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang
dilakukan oleh pasukan yang berada dibawah komando dan pengendaliannya yang
efektif atau dibawah kekuasan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana
tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengandalian pasukan secara
patut…..”.
Penggunaan kata dapat dan bukannya kata akan
atau harus, telah menyebabkan bahwa
tanggungjawab komando dalam kasus pelanggaran HAM berat tidak bersifat wajib,
tapi lebih dibebankan kepada pelaku langsung di lapangan (dalam hal ini para
anak buah/prajurit dilapangan);
2. Disamping persoalan-persoalan
adopsi/penerjemahan yang tidak sesuai yang penulis sebutkan diatas (lepas
apakah hal itu disengaja atau tidak), terbukti telah menyebabkan munculnya
pengertian/penafsiran yang berbeda pada isi pasal-pasal yang ada dalam UU No.
26/2000 dengan ketentuan yang ada pada Statuta Roma yang dijadikan
dasar/rujukan. Tapi yang tidak kalah penting adalah tidak adanya/tidak
dicantumkannya apa yang disebut sebagai element
of crimes di dalam UU Peradilan HAM.
Karena dalam element of crimes itulah
secara jelas terdapat elaborasi atas unsur-unsur, definisi-definisi dan bentuk
kejahatan terhadap kemanusiaan, sehingga perbedaan penafsiran maupun interpretasi
dalam hal ini bisa diminimalkan.
Dari urain di atas kita dapat melihat bahwa UU
tentang HAM yang berlaku di Indonesia masih sangatlah lemah dalam menjerat para
pelaku kejahatan HAM sebagai akibat masih adanya multitafsir terhadap
Undang-undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM akibatnya banyak pelaku
pelanggar Hak Asasi Manusia yang tidak dapat di proses terutama para Komando
Militer karena mereka masih mempunyai cela dalam memahami frasa kata yang
terdapat dalam Undang-undang tersebut
hal ini pasti akan berimplikasi kepada praktek impunitas yang makin tumbuh subur
dalam sistem hukum Indonesia.
BAB III
METODE
PENELITIAN
3.1. Jenis Penelitian
Penelitian hukum normatif (normative
law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku
hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang
dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang belaku dalam masyarakat dan menjadi
acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada
inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam
perkara in concreto, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan
hukum dan sejarah hukum.[48]
Penelitian ini
merupakan penelitian hukum normatif yakni Kajian Yuridis Terhadap Asas
Pertanggungjawaban Komando Suatu Kajian Kritis terhadap kasus semanggi
Penelitian ini menganalisis kedua rumusan masalah secara normatif. Analisis
dengan cara normatif dilakukan dengan cara kajian kepustakaan dan literatur
terkair terkait penegakan asas Pertanggungjawaban Komando yang belum di
laksanakn secara optimal di Indonesia.
Penelitian hukum
normatif atau penlitian hukum doctrinal, yaitu penelitian hukum yang
menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh dari bahan-bahan
kepustakaan.[49]
3.2. Pendekatan
Penelitian
Peneliti dalam penelitian ini akan menggunakan
beberapa pendekatan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, yakni:[50]
1.
Pendekatan
Historis (Historical Approach)
Pendekatan
historis dilakukan dalam kerangka sejarah lembaga hukum dan perkembangan
pemikiran hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti
memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu, melalui
pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan
perkembangan filosofis yang melandasi aturan hukum tersebut. Dalam pendekatan
historis ini, maksud calon peneliti adalah melihat tujuan di berlakukanya Asas
Peratnaggungjawaban Komando di dunia dan khusunya Indonesia.
2.
Pendekatan
Perundang-Undangan (Statute Approach)
Dalam metode pendekatan
perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam
peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan
tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat negara melalui prosedur yang
ditetapkan dalm peraturan perundang-undangan.[51] Dari
pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai
statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan
perundang-undangan adalah pendekatan menggunakan legislasi dan regulasi. Selain
itu penulis juga akan melakukan pendekatan peraturan Internasional seperti
Konvensi, Traktat, Statuta Roma (ICC), Peraturan Pengadilan Ad hoc.
Peraturan perundang-undangan yang dapat
digunakan dalam penelitian ini adalah:
1)
Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2)
Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
4)
Peraturan
Pemerintah
Peraturan Internasional yang di
gunakan di penelitian ini adalah:
1) Konvensi
2) Traktat
3) Statuta
Roma (ICC)
4) Pengadilan
Internasional Ad hoc
3.
Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual
dilakukan manakala calon peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada.
Hal ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah
yang dihadapi. Dalam pendekatan ini, calon peneliti memikirkan bagaimana seharusnya
permasalahan ini dijawab setelah dilakukan penelitian menggunakan metode
pendekatan historis dan pendekatan pernudang-undangan.
3.3. Bahan Hukum
Pada penelitian hukum tidak dikenal
adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber
penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu
dikenal istilah bahan hukum.[52] Penelitian
hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian
umumnya disebut bahan hukum sekunder.[53]
Bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi atas primer dan
sekunder:
1.
Bahan
Hukum Primer
Bahan hukum primer
merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, dalam penelitian ini terdiri
dari;
a. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. TAP MPR No. XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia.
c. Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
d. Undang-Undang
No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
e. Keputusan Presiden Nomor 40 tahun
2004.
f. Peraturan Presiden Nomor 23 tahun
2011.
g. Konvensi Den
Haag IV 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat.
h. Konvensi
jenewa I Tahun 1949 tentang Tanggung Jawab Negara.
i.
Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun
1977.
j.
Statuta
International Criminal Court (ICC).
k. International
Criminal tribunal for the former Yugoslavia.
l.
International
Military Tribunal/IMT) Nurenberg.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder
merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer
dalam penelitian. Bahan hukum sekunder berfungsi memperkuat penjelasan. Bahan
hukum sekunder dapat bersumber dari buku-buku, jurnal, skripsi, tesis,
disertasi atau hasil-hasil penelitian lainnya.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier
merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat bersumber dari dari
Blibliografi, Indeks Kumulatif, Kamus-Kamus maupun akses internet yang
kredibel.[54]
3.4. Teknik
Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan
bahan hukum dalam sebuah penelitian normatif dilakukan dengan cara telaah
arsip, dokumen perundang-undangan atau studi pustaka seperti buku-buku, jurnal,
skripsi, tesis, disertasi atau publikasi hasil penelitian lainnya.
3.5. Analisis Bahan
Hukum
Teknik analisis bahan
hukum yang digunakan adalah hermeneutika hukum. Hermeneutika hukum sendiri
adalah metode penafsiran hukum yang ditijukan untuk mendapatkan kejelasan dari
suatu hal. Tahapan analisis bahan hukum, diawali dengan pengumpulan bahan hukum
primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa konstitusi, undang-undang,
sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, dan publikasi hasil penelitian.
Bahan hukum primer dan sekunder ditelaah dan dianalisis sehingga melahirkan
suatu konsep yang berkaitan dengan judul penelitian tersebut.[55]
DAFTAR
PUSTAKA
BUKU
Asshiddiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,
Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
Atmasasmita
Romli, Perbandingan Hukum Pidana, cetakan pertama, Mandar Maju, Bandung,
2000.
Arinanto Satya, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Cetakan ke
II , Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, 2005
Abidin Zainal , Pengadilan Hak Asasi Manusia
Di Indonesia, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007.
Budiardjo
Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama, 2008.
Fajar ND Mukti dan Achmad
Yuliyanto, Dualisme Penelitian Hukum
Normatif & Empiris, Yogyakarta:, 2010.
Moeljatno, Asas-Asas
Hukum Pidana,cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
Marzuki Peter, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Surabaya:
Prenadamedia Group, 2005
…………………Penelitian
Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
Marwan. M dan P. Jimmy, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya,
2009
Muhammad
Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Cetakan 1. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2004.
Starke.
J.G , Pengantar Hukum Internnasional Cetakan
ke Sepuluh, Jakarta Sinar
Grafika, 2010.
Soekanto Soerjono dan
Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif
Tinjauan Singkat, Jakarta:
Rajawali Pers, 2006.
Suratman
dan Dillah H. Philips, Metode Penelitian
Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013
Saleh Roeslan,
Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana, Ghalia Indonesia,
1982.
Wibowo
wahyu , Pengantar Hukum Hak Asasi
Manusia, Pusat Studi Hukum Militer, Jakarta, 2014
Peraturan
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 26
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Keputusan Presiden Nomor 40 tahun
2004.
Peraturan Presiden Nomor 23 tahun
2011.
Konvensi Den Haag IV 1907 tentang Hukum
dan Kebiasaan Perang di Darat.
Konvensi jenewa I Tahun 1949
tentang Tanggung Jawab Negara.
Protokol Tambahan I
Konvensi Jenewa tahun 1977.
Statuta
International Criminal Court (ICC).
International Criminal tribunal for
the former Yugoslavia.
International
Military Tribunal/IMT) Nurenberg.
Jurnal
Hukum
Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Kertas Kerja: Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma
Tentang Mahkamah Pidana Internasional ,2008.
Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM), Tanggung Jawab
Komando Suatu Telaah Teoritis. Jakarta: ELSAM, 2005
Natsri Anshari, Dalam Artikel Tanggung
Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia, Jurnal
Hukum Humaniter Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005.
Fadillah Agus, dalam makalah Tanggung
jawab Komando oleh Vonny A.
Wongkar ,Tanggung
Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Dan Kejahatan
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia. 2009.
Lembaga Studi dan Advokasi (ELSAM)
Masyarakat Makalah Kejahatan Terhadap kemanusiaan, 2008.
Internet
https://id.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87
Di akses tanggal 17 November 2016. Pukul 13.00. WITA.
h.;ttp://osdir.com/ml/culture.region.%20indonesia.ppi-india/2005-03/msg00596.html diakses tanggal 17
November 2016.
https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bosnia
Di akses tanggal 17 November 2016, Pukul 12.30. WITA.
https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi.
Di akses tanggal 21 November 2016. Pukul 13.33 WITA.
http://kbbi.web.id/kaji
Di akses tanggal 21 November 2016, pukul 15.00. WITA).
http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab
(Di akses tanggal 17 November 2016, pukul 10.00. WITA).
[1] .Starke, Pengantar Hukum Internnasional, (Jakarta Sinar Grafika, 2010), Hal
8.
[2] Ibid. hlm. 17
[3] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia
Pustaka Utama 2008, Hal 211.
[4]Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Bosnia Di akses tanggal 17 November
2016, Pukul 12.30. WITA.
[6] Ibid
[7] Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Semanggi. Di akses tanggal 21 November
2016. Pukul 13.33 WITA.
[8]Koalisi
Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional, Kertas Kerja: Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma
Tentang Mahkamah Pidana Internasional Tahun 2008.
[11] Lihat. Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,Pasal 28 I ayat 4.
[12] Lihat. Undang-undang No. 26
tahun 2000 pasal 1 angka 3.
[14] M. Marwan dan Jimmy P. 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, h. 651.
[15] Lihat. http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab (Di akses tanggal 17 November
2016, pukul 10.00. WITA).
[16]Roeslan Saleh, Pikiran-Pikiran
Tentang Pertanggungja waban Pidana, 1982, Ghalia Indonesia, hal.33-34.
[17] Romli Atmasasmita, Perbandingan Hukum
Pidana, cetakan pertama, 2000, Mandar Maju, Bandung,hal. 65.
[20] Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Tanggung Jawab Komando Suatu Telaah Teoritis.
(Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 4
[21] Lihat. Protokol Tambahan I
Konvensi Jenewa 1977 Pasal 86 ayat (2) AP I.
[24] Wahyu, Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia, Pusat
Studi Hukum Militer, Jakarta,
2014. Hal 208-209.
[25] Ibid. hlm. 209.
[26] Ibid. hlm. 209-210.
[27] Natsri Anshari, Dalam Artikel Tanggung
Jawab Komando Menurut Hukum Internasional dan hukum nasional Indonesia, Jurnal
Hukum Humaniter Vol.1 No.1, Edisi Juli 2005. Hal. 50-51.
[28] Ibid. hlm. 51-52.
[29] Ibid. hlm. 52
[30] Ibid. hlm. 53-54.
[31] Fadillah Agus, dalam makalah Tanggung
jawab Komando oleh vonny (2009). Tanggung
Jawab Komando Terhadap Pelanggaran Hak
Asasi Manusia Yang Berat Dan Kejahatan
Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia.
Hlm. 67.
[32] Pasal 49 dan Pasal 50 berbunyi
sebagai berikut: Pasal 49: Pihak peserta agung berjanji untuk menetapkan
undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap
orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu
diantara pelanggarana berat atas konvensi ini seperti ditentukan di dalam pasal
berikut. Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang
disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan
pelanggaran-pelanggaran berta yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang
tersebut, dengan tidak memandang kebangsannya. Pihak Peserta Agung dapat juga,
jika dikehendakinya,dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya
sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan,
orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat
menunjukkan suatu perkara prima facie. Tiap Pihak Peserta Agung Harus
mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran
berat yang ditentukan dalam pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Dalam segala keadaan, orang-orang yang
dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang
tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh
Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan perang tanggal 12 Agusrus 1949
sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan seterusnya.
Pasal 50: Pelanggaran-pelanggaran berat
yang dimaksudkan oleh pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang
meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang
atau milik yang dilindungi oleh konvensi:pembunuhan disengaja, penganiayaanatau
perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis,
menyebebkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau
kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan perampasan atas harta
benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan
dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.
a.Kejahatan Perdamaian; kejahatan
terhadap perdamaian adalah perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan
perang agresi, atau peperangan yang melanggar perjanjian internasional, atau
ikut serta dalam suatu konspirasi untuk melakukannya;
b.Kejahatan Perang; pelanggaran
terhadap hukum-hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang.ͨ : pembunuhan, perlakuan
buruk, deportasi, perbudakan, perampasan, dan penghancuran;
c.Kejahatan Kemanusiaan; adalah
pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, dan tindakan-tindakan tidak
manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap populasi sipil, sebelum atau selama
perang berlangsung, atau penganiayaan atas dasar politik, rasial atau keagamaan
dalam pelaksanaan atau dalam hubungannya dengan kejahatan apapun dalam
yurisdiksi Mahkamah, baik yang dianggap melanggar atau tidak melanggar hukum
domestik di negara tempat kejahatan itu dilakukan.
[34] Lihat. ICTY (International Criminal tribunal
for the former Yugoslavia). Pasal 6 ayat 3 dan pasal 7 ayat 3.
[35]Lihat. https://id.wikipedia.org/wiki/Slobodan_Milo%C5%A1evi%C4%87 Di akses tanggal 17 November
2016. Pukul 13.00. WITA.
[37] Ibid.
[38] Ibid.
[39] Lihat. penjelasan Pasal 104 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999
junto penjelasan Pasal 7 UU No. 26 Tahun 2000.
[41] Satya Arinanto, Hak
Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, cet. II, (Jakarta: Pusat
Studi Hukum Tata Negara, 2005), hlm. 32
[42] Zainal
Abidin, Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, (Jakarta: Lembaga
Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007), hlm. 4-5
[43]Lihat. h.;ttp://osdir.com/ml/culture.region.%20indonesia.ppi-india/2005-03/msg00596.html diakses tanggal 17 November 2016.
[44] Lihat Pasal 7 Statuta Roma
Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusian.
[47] Lihat Pasal 42 Ayat 1 UU No. 26
tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
[48] Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum dan Penelitian
Hukum. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 52
[49] Mukti Fajar ND
dan Yuliyanto Achmad, Dualisme Penelitian
Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta:, 2010), hal 154.
[50] Peter Mahmud
Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi,
(Surabaya: Prenadamedia Group, 2005), hal.136-176
[51] Pasal 1 angka 2 Undang-undang
No.12 Tahun 2011 tentang Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
[52] Peter Marzuki, Penelitian Hukum, (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti), 2004), hal. 41
[53] Soerjono
Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian
Hukum Normatif Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hal. 24
[54] Suratman dan H.
Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum,
(Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 67
[55] Jimly
Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata
Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hal. 308


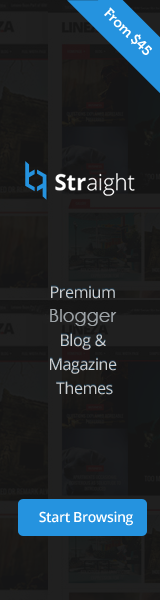
Tidak ada komentar